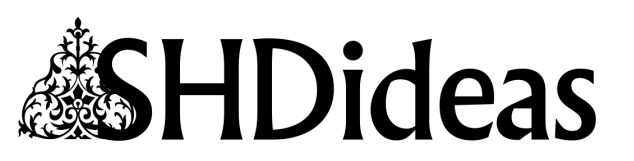Sebagai bangsa yang secara historis maupun genealogis penerus dan pewaris DNA bangsa besar, yaitu bangsa Nusantara maka lahir dan terbentuknya Indonesia tidak mungkin tidak mengaitkan kiprah kerajaan-kerajaan di Nusantara masa lalu. Bukan semata karena Soekarno dalam pidato terakhirnya sebagai presiden pada HUT ke-21 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1966 dengan lantang menyerukan “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah” (Jasmerah) saja. Tetapi tautan kita dengan aneka peritiwa masa lalu juga penting agar sebagai bangsa tidak kita tercerabut dari akar sejarahnya. Berdasar cakupan luasnya wilayah, besarnya pengaruh, dan karya-karya agung yang ditorehkan, periodisasi sejarah Nusantara terbagi tiga, yaitu era negara Nusantara I/ Sriwijaya (671-1183), negara Nusantara II/ Majapahit (1293-1478), dan negara Nusantara III/ NKRI (1945-sekarang). Dengan kata lain proses membangsa-menegara Indonesia sejatinya telah berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun.
Kata Sahabat

Laksda Purn TNI Untung Suropati
KETIKA KUTERINGAT NAMA SEORANG KAWAN SEPERJUANGAN
Kita patut berbangga karena pada masanya Sriwijaya dan Majapahit pernah mencapai status negara adidaya. Menariknya Majapahit hanya perlu waktu kurang dari 75 tahun untuk mencapai status sebagai negara besar, kuat, dan disegani tersebut. Pasca-runtuhnya Majapahit meninggalkan “Lima Warisan Agung” yang terlupakan, yaitu: a) “Rumah besar” bernama Indonesia, b) Bendera “Merah Putih”, c) Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, d) Lencana Perang–diadopsi TNI AL, e) Moto dan simbol yang masih banyak digunakan Kementerian/ Lembaga termasuk TNI/ Polri hingga hari ini. Sayang 500 tahun berlalu, dalam kurun waktu yang sama, anak cucunya yang kini menyebut dirinya bangsa Indonesia masih tertatih-tatih. Alih-alih adidaya, Bumi Surgawi, Indonesia Emas atau apalah namanya. Pastinya fakta menunjukkan betapa proses pencarian identitas dan jati diri sebagai bangsa yang berdasar dan ber-way of life Pancasila saja masih belum kunjung ketemu atau terbentuk. Ironis.
Padahal sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 setiap pemimpin atau pemerintahan telah mengerahkan segenap kemampuan dan kebijakan atau program terbaiknya. Contoh Soekarno dengan gebrakannya, yaitu “Revolusi Mental” yang digaungkan tanggal 17 Agustus 1956. Soeharto dengan gerakan antitesisnya yang khas dan unik, yaitu melaksanakan (kembali) Pancasila dan UUD NRI 1945 secara murni dan konsekuen. B.J. Habibie dengan kebijakannya berani, seperti Pemilu bebas dan demokratis, kebebasan pers, dan otonomi daerah. Demikian pula presiden-presiden selanjutnya. Tetapi sebagaimana kita saksikan hasilnya masih sangat jauh dari harapan–kalau tidak boleh dikatakan nol besar. Buktinya indeks intoleransi, diskriminasi hukum, politik uang, pelanggaran Pemilu, pembusukan demokrasi, dan korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) makin marak. Ujung-ujungnya siapa lagi kalau bukan wong cilik alias rakyat yang jadi korban atau menanggung akibat.
Pada titik inilah saya teringat sebuah nama: Mas Setyo. Lengkapnya Mas Setyo Hajar Dewantoro. Kawan seperjuangan. Nama yang lekat sekaligus mengingatkan saya pada seorang tokoh besar. Tokoh pendidikan yang juga pejuang kemerdekaan Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Seperti telah disebutkan bahwa karut-marutnya negeri ini karena sejatinya bangsa Indonesia sedang “sakit”. Dampak krisis identitas dan jati diri. Penyakit yang tanpa disadari terus menggerogoti. Konsekuensi logis bangsa yang durhaka pada leluhurnya. Sebagaimana tesis Jüri Lina dalam bukunya “The Architects of Deception”. Bahwa selain dengan kekuatan militer (hard power), penghancuran suatu negara juga bisa dilakukan dengan cara-cara non-militer (soft power), yaitu: a) Kaburkan sejarahnya; b) Hancurkan situs, artefak, dan bukti-bukti pendukungnya; c) Putuskan hubungan dengan leluhur. Sejarah mencatat dampak penghancuran dengan cara ini di banyak negara bahkan jauh lebih masif dan mengerikan.
Kenapa teringat tentu bukan tanpa sebab. Selain paradigma dan cara pandang, kesamaan visi perjuangan juga membuat kebersamaan kami senantiasa terjaga. Momen-momen penting dan bersejarah bahkan terukir sejak awal kami saling mengenal. Contoh deklarasi bersama “Gerakan Kembali ke Nusantara” (GKKN). Sebuah gerakan moral demi memperjuangkan kembalinya kekitaan kita atau keindonesiaan Indonesia yang makin memudar. Bertempat di situs Petirtaan Jolotundo yang terletak di lereng sisi barat Gunung Penanggungan, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur pada hari Sukra Cemengan, 14 Kresnapaksa, 1939 Saka atau Jumat Wage, 19 Januari 2018. Selanjutnya Pasamuan Agung “Komunitas Pejalan Suwung” bertema “Retrospeksi Membangun Harmoni Menuju Kejayaan (kembali) Indonesia” di Padepokan Pengging, Desa Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten/ Kota Magelang, Jawa Tengah. Puncak acara digelar di puncak Gunung Tidar pada hari Sabtu Kliwon, 14 Juli 2018.
Waktu terus berputar, hari dan bulan pun terus berganti. Setelah cukup lama tidak bertemu kini yang terjadi dan saya lihat seorang Mas Setyo baru. Bukan lagi seperti spiritualis-budayawan yang saya kenal ketika itu. Semangat, konsistensi, dan determinasinya yang luar biasa sepertinya telah membawa banyak perubahan sekaligus capaian (achievement). Bukan hanya ruang gerak aktivitas spiritualnya yang kini “Go International” meluas nun jauh hingga ke negeri seberang–negara-negara Asia dan Eropa. Tetapi berbagai potensi lain yang dimiliki juga telah jauh berkembang. Contoh bakat kepemimpinan, jiwa kewirausahaan, kemampuan menulis, kepekaan dan kepedulian terhadap upaya penyelamatan lingkungan, dan masih banyak lagi. Fakta ini sekaligus menggugurkan pandangan pada umumnya bahwa dunia spiritual identik dengan bakar menyan, pakaian serba hitam, dan penampilan seram. Kesan yang kadang tanpa sadar diciptakan justru oleh para pejalan spiritual dan penggiat budaya sendiri.
Sebagai seorang entrepreneur, penulis banyak buku–bergenre spiritualisme, dan pemikir masalah-masalah kebangsaan berlatar belakang guru spiritual, kehadiran Mas Guru–demikian Mas Setyo biasa dipanggil di kalangan murid-murid atau komunitasnya–menjadi penting dan dibutuhkan. Kenapa? Karena sumber krisis tiada lain hati dan pikiran. Hati dan pikiran yang “berdebu” alias tidak sehat. Sementara sebagai seorang spiritualis Mas Guru tentulah memiliki kepedulian sekaligus keterpanggilan untuk senantiasa hadir dan “membersihkan” atau menyembuhkan. Sebagai purnawirawan TNI dengan masa pengabdian 35 tahun–lima tahun di antaranya (terakhir) berdinas di Lemhannas RI–dan dengan GKKN tengah berjuang demi kembalinya identitas dan jati diri bangsa, demi kembalinya keindonesiaan Indonesia, saya melihat sosok Mas Guru adalah aset bangsa. Sekarang tinggal bagaimana potensi yang dianugerahkan oleh-Nya untuk senantiasa dipupuk dan dikembangkan agar kapasitas dan kapabilitas dirinya terus meningkat dan terasah. Sehingga siap didedikasikan sewaktu-waktu untuk kepentingan yang lebih besar.