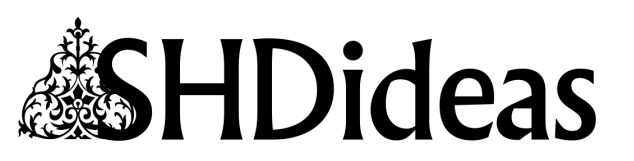Terminologi “Tahta untuk Rakyat”, dinyatakan dan dipopulerkan oleh Sinuwun Hamengku Buwono IX yang merupakan salah satu Raja Jawa dan bertahta di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu bukan sekadar kata-kata tapi memang merupakan prinsip kepemimpinan yang ia jalankan. Sangat terkenal cerita bagaimana sebagai seorang Raja ia tak sungkan untuk menyopir mobil sendiri. Suatu saat ia memberi tumpangan pada simbok-simbok pedagang pasar yang kemudian ngedumel karena sang sopir yang telah memberi jasa tak mau dibayar. Simbok-simbok itu tak sadar baru saja diberi tumpangan oleh seorang Raja Jawa yang memang sangat rendah hati dan penuh kasih.
Lalu apa sebenarnya arti dari “Tahta untuk Rakyat”? Ini adalah filosofi kepemimpinan bagi para negarawan bahwa kekuasaan yang dia pegang, harus dipergunakan untuk melayani, melindungi, mengayomi dan mensejahterakan rakyat. Filosofi ini tentu semakin relevan di sebuah Republik seperti Indonesia, yang memiliki prinsip kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan bahwa setiap pemimpin pada dasarnya menerima mandat dari rakyat (atau institusi yang mewakilinya).
Tapi sayang sekali praktik kepemimpinan di Indonesia saat ini, setelah 79 tahun menjadi Republik, jarang sekali mengalami momen realisasi prinsip “Tahta untuk Rakyat”. Jarang sekali dan sedikit sekali pemimpin di tingkat nasional maupun daerah yang konsisten membela kepentingan rakyat dengan melampaui kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan bohirnya. Jika melihat bagaimana kebijakan pemberian ijin pengelolaan tambang yang biasanya diikuti dengan deforestasi, ijin pembukaan kebut sawit yang juga diiringi deforestasi, biasanya rakyat jadi pelengkap penderita – termasuk masyarakat lokal jadi kehilangan akses terhadap hutan adat dan tanah ulayat mereka. Kebijakan Proyek Strategis Nasional juga secara faktual acapkali menempatkan rakyat di posisi yang rentan: dalam banyak kasus mereka harus tergusur dari tanah yang mereka tempati bergenerasi – generasi.
Kepemimpinan nasional dan daerah yang lahir dari rahim demokrasi (liberal/pasar) ternyata umumnya mengecewakan; sistem yang sering diglorifikasi aktivis, pakar, sekaligus politisi pro demokrasi ini sama sekali tak memberi jaminan kemunculan kepemimpinan yang menjalankan prinsip “Tahta untuk Rakyat”. Seringkali yang terjadi adalah kebalikannya: ” Rakyat (dimanipulasi) untuk Tahta”, rakyat cuma dipakai suaranya saat Pemilu/Pilkada dengan bujuk rayu lalu ditinggalkan para politisi setelah mereka meraih tahta.
Saya jelas rindu pada Raja Jawa yang adil dan bijaksana, yang penuh kasih dan melayani rakyat, seperti Sinuwun Hamengku Buwono IX. Memang jelas tak semua raja seperti beliau. Tapi jelas pula sistem kerajaan tak selamanya buruk sebagaimana kita juga harus kritis bahwa janji manis kehebatan sistem demokrasi (pasar/liberal), selama Orde Reformasi ini belum juga terbukti.
Sesungguhnya di dunia ini juga masih banyak yang memberlakukan sistem monarki/kerajaan, baik yang murni maupun dikombinasi dengan demokrasi: Inggris, Belanda, Spanyol, Negara-negara Skandinavia dan Timur Tengah, hingga Kamboja, Thailand, Malaysia dan Brunei. Ya mari kita lihat bagaimana korelasinya dengan kesejahteraan rakyat dikomparasikan dengan negara-negara yang sepenuhnya menerapkan sistem demokrasi.
Tentu bukan maksud saya menarik mundur Indonesia agar menjadi kerajaan kembali. Karena ini juga perkara rumit yang berbeda dengan kesepakatan para pendiri Indonesia. Tapi kita bisa belajar bagaimana seorang Raja Jawa di masa lalu betul-betul bisa menjalankan prinsip Tahta untuk Rakyat. Ini sebetulnya terkait dengan proses menjadi pemimpin yang didahului dengan penggemblengan sehingga seorang calon Raja bisa memiliki karakter Satria Pinandhita Sinisihan Wahyu yang lalu memiliki kelayakan untuk menerima Wahyu Keprabon dalam segala bentuknya: Wahyu Makutha Rama dan segala kategori wahyu lainnya, yang menyimbolkan dukungan penuh semesta (termasuk para leluhur) kepada sang pemimpin.
Pemimpin yang sungguh-sungguh menerima Wahyu Keprabon tentu saja akan punya kemurnian hati dan dianugerahi banyak kemampuan mulai dari kharisma kepemimpinan, kecerdasan sebagai negarawan, kekuatan untuk melebur keangkaramurkaan, hingga kekuatan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Dikaitkan dengan tradisi mistik Jawa, pemimpin yang hebat pastilah punya Trisula Wedha: Kemampuan Magis, Kecerdasan/Intelektualitas, dan Kekayaan Material yang membuatnya bisa menjalankan kepemimpinan secara efektif.
Jika kita tak hendak mengubah Republik menjadi Monarki/Kerajaan, maka perjuangan kita adalah memunculkan pemimpin berkarakter Satria Pinandhita Sinisihan Wahyu yang memiliki Pusaka Trisula Wedha. Tentu yang bisa memenuhi kriteria ini adalah orang-orang yang tekun menjalankan laku spiritual murni dan menggembleng dirinya dengan sungguh-sungguh dalam arahan Gusti yang bertahta di relung hati.
Mungkinkah yang seperti ini bisa terjadi? Ya mungkin saja. Kita hanya harus berupaya sungguh-sungguh dan menunggu momentum datang. Pasti ada waktunya panggung politik kita dibanjiri para Satria Pinandhita Sinisihan Wahyu.